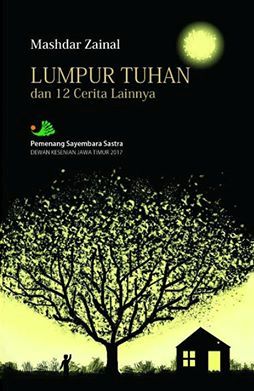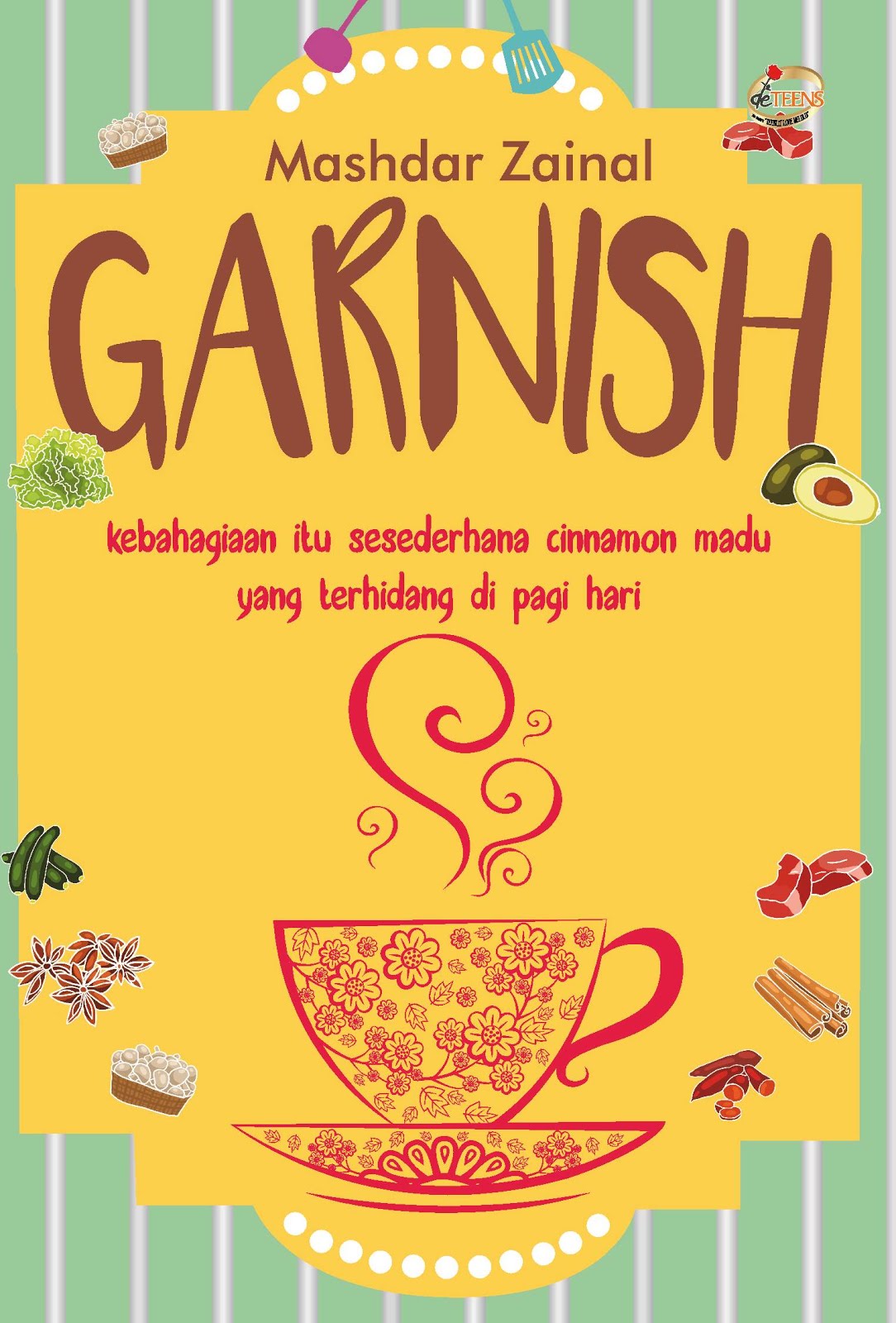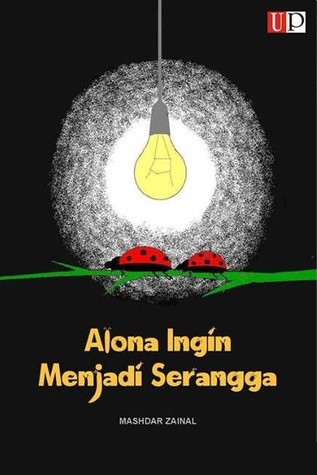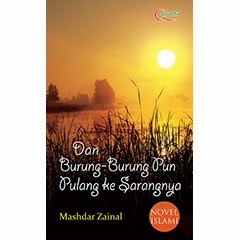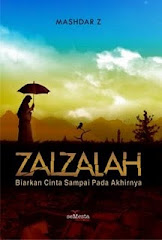Rumah kami tidak
terlalu besar, tapi juga tidak bisa dibilang kecil. Rumah kami memuat 3 kamar
yang masing-masing berukuran 4x5 meter, 3 kamar madi, sebuah ruang
keluarga—tempat anak-anak menonton TV, sebuah ruang baca sekaligus perpustakaan
pribadi, sebuah dapur yang bersebelahan dengan garasi, dan sebuah ruang tamu
berukuran 4x6 meter. Di depan rumah ada taman yang tidak terlalu luas, tapi
lebih dari cukup untuk ditanami berbagai macam bunga serta membuat pancuran dan
kolam ikan. Di rumah, kami tinggal berlima. Saya dan istri, dua putra kami yang
semuanya masik duduk di bangku SD (yang besar sudah kelas empat, yang kecil baru
masuk kelas satu), dan seorang khadimah
yang bertugas memasak dan mengurus rumah.
Rumah kami terasa mati meski
tak pernah sepi. Setiap hari jerit anak-anak dan suara bising Play Station sudah
menyambut kami setiap kali pulang kerja di sore hari. Rumah kami juga terang
benderang, lampu-lampu besar berhias kristal menempel dan menggantung di
mana-mana, namun dalam hati kecil kami, kami merasa rumah kami sangat redup dan
suram.
***
Suatu malam, sepulang
dari pengajian, kami langsung ambruk di pembaringan. Bahkan aku tak sempat
mengucapkan selamat malam pada istriku. Begitu juga dia. Kami sama-sama letih.
Dan pada malam itulah—jauh selepas malam, lelaki itu datang. Kami mendengar bel
berbunyi. Sesekali sayup-sayup suara pintu diketuk. Aku tak menggubris sama
sekali. Biasanya, sekali saja ada bel berbunyi, pembantuku yang akan langsung
membukakan pintu. Tapi aneh sekali, lebih dari lima kali, dan bel itu masih
terus berbunyi, diiringi ketukan pintu sesekali. Terpaksa aku bangkit dari
tidur sambil mengumpat dalam hati.
“Siapa sih, bertamu
malam-malam begini. Tak tahu aturan.” gumamku masih setengah sadar.
Aku berjalan
sempoyongan, mendekati pintu. Dengan mata yang masih setengah mengatup, kutarik
grendel pintu. Kutarik gagang pintu itu pelan-pelan—telah kusiapkan pula muka
masam. Dan mataku terbelalak ketika daun pintu telah kubuka lebar. Seorang
lelaki dengan perawakan tinggi sudah beruluk salam sambil melempar senyum.
Entah bagaimana kujelaskan ketampanannya, dibalik kulit wajahnya seperti
tersimpan butiran cahaya yang terus berpendar. Entah musabab apa, aku seperti
tersihir oleh cahaya di wajahnya. Maka rasa kantukku seperti hilang begitu
saja, hatta lelaki itu kupersilahkan masuk. Ketika aku hendak beranjak untuk
memanggil pembantuku—supaya membuatkan segelas teh atau kopi, lelaki itu
melarangku.
Lelaki itu mengaku bernama
Ahmad. Ia bilang, ia mengenalku, bahkan ia bersikeras menyatakan bahwa aku juga
sangat mengenalnya. Entahlah, setelah kutilik wajahnya beberapa kali, aku
memang merasa pernah mengenalnya, bahkan sangat mengenalnya. Namun entah kapan,
entah di mana, aku lupa.
“Maaf, sudah menggangu
istirahat, Tuan.” Tuturnya lembut.
“Oh, tidak apa-apa.
Ngomong-ngomong ada keperluan apa bertamu malam-malam begini, apa ada sesuatu
yang sangat mendesak.” Balasku.
“Oh, tidak, saya hanya
ingin bermalam saja di rumah Tuan yang hangat ini.”
Pernyataanya
sesungguhnya cukup ganjil, bagaimana mungkin ada orang ingin menginap di rumah
orang lain tanpa alasan yang jelas, datang malam-malam buta pula. Namun
lagi-lagi, entah kenapa, semua yang meluncur dari mulutnya terasa benar dan tidak
mengada-ada.
“Memangnya Tuan berasal
dari mana.” Aku mencoba mengorek sesuatu tentang dirinya.
“Tuan tahu saya dari mana.
Hanya saja Tuan lupa.” Balasnya enteng. Namun lagi-lagi, aku tidak
memperslahkannya. Semua yang meluncur dari mulutnya terdengar mantap.
“Sebentar, sebentar,
siapa ya?” aku mengetuk-ketuk jidadku sendiri. Kupicingkan mata ke lelaki itu.
Dan lelaki itu hanya tersenyum.
“Tak perlu dipaksa,
nanti Tuan juga akan tahu siapa saya.”
“Siapa, ya?” aku masih
penasaran.
“Mmm… bolehkan saya numpang
sholat sunnah. Apa ada mushola di rumah Tuan?” ucapnya tiba-tiba.
Aku terantuk, dan tak
tahu harus menjawab apa, “oh, maaf. Tak ada mushola khusus di rumah saya. Saya
menggelar sajadah di sebelah ranjang, dan biasanya saya sholat di sana.”
“Oh tidak apa-apa.
Sholat bisa di mana saja.”
Segera saya antar
lelaki itu ke kamar tamu, saya ambil sajadah yang masih terlipat dalam lemari.
“Silahkan!” lirihku.
Lelaki itupun menggelar
sajadahnya ke arah kiblat. Aku mengintip ia dari balik pintu. Beberapa kali aku
menepuk kepala, mengingat-ingat, kapan terakhir kali aku sholat malam. Sebulan
yang lalu? Setahun yang lalu? Dua tahun yang lalu? Lima tahun yang lalu?
Entahlah! Aku benar-benar lupa. Tiba-tiba aku merasa sangat malu pada diriku
sendiri.
Hampir setengah jam aku
menunggunya di ruang tamu. Aku kembali terkantuk-kantuk.
“Kalau Tuan mengantuk.
Sebaiknya Tuan istirahat saja.” Suaranya membuatku terhenyak.
“Oh, sudah selesai.
Tidak, saya tidak mengantuk.”
“Maaf, apa Tuan ada
Al-Quran?” ia kembali bertanya.
“Al-Quran?” Aku
tertohok. “Oh ya, sebentar-sebentar.” Aku bangkit dan berjalan ke dalam kamar.
Aku sudah mulai deg-degan. Jujur, aku tidak tahu apakah di rumahku ada Al-Quran
atau tidak. Tapi aku terus mencari. Mustahil seorang muslim tak punya Al-Quran
di rumahnya. Aku terus mencari, membongkar lemari dan buku-buku. Hingga kitab
itu kutemukan di antara tumpukan buku-buku lawas yang tak pernah kubaca. Ia
begitu usang dan berdebu. Aku memeluk kitab itu dengan lega, dan entah kenapa
aku ingin menangis. Segera aku berlari memui lelaki itu di ruang tamu. Ia masih
di sana, matanya terpejam, tapi mulutnya merapal surah-surah yang tak kutahu.
“Maaf. Ini
Al-Qurannya.” Kuserahkan kitab itu padanya dengan tangan gemetar. Tapi lelaki
itu tersenyum. Ia mulai membuka mushaf itu dan membacanya. Ia sudah membaca
beberapa ayat saat aku menyelanya.
“Maaf. Nanti kalau Tuan
hendak instirahat, silahkan beristirahat di kamar tamu saja. Anggap saja rumah
sendiri.” Kataku, sebelum memohon diri untuk kembali ke kamar.
Aku berjalan lesu ke
kamar. Kulihat istriku masih mendengkur. Dari dalam kamar. Kudengar suara
lelaki itu melantunkan ayat-ayat dengan sangat sempurna dan merdu. Entah kenapa
aku tak bisa tidur lagi. Ingin kubangunkan isteriku, tapi melihat tidurnya yang
sangat pulas, niat itu kuurungkan.
Pikiranku kemali pada
lelaki itu, lelaki yang bertamu malam-malam dan sekarang tengah membaca mushaf
di ruang tamu. Hal itu seharusnya sangat aneh. Sangat sangat aneh. Tapi tidak
untuk malam itu. Kucoba utuk memejamkan mata kembali, namun gagal. Maka
kuputuskan untuk kembali ke ruang tamu. Di sana, lelaki itu masih duduk terpaku
dengan mushaf di pangkuanya. Ia melihatku datang, lantas ia menyudahi bacaanya.
Ia bagai bersiap-siap untuk kuajak berbincang-bincang panjang.
“Rumah Tuan lumayan
besar, ya!” komentarnya tiba-tiba.
“Yah… Alhamdulillah.
Ini patut saya syukuri.”
“Tuan suka membaca?”
Tanyanya lagi.
Tiba-tiba aku sangat
bersemangat dengan pertanyaannya, “ouh, aku punya perpustakaan pribadi.”
Sambutku girang. “Mau melihat-lihat?” lanjutku.
“Dengan senang hati.”
Balasnya singkat, tetap tersenyum.
Aku bangkit dan
melenggang menuju perpustakaan pribadi kebangganku. Sampai di ruang buku,
lelaki itu kembali berkomentar, “Wow, buku Tuan banyak sekali. Buku apa saja
ini?”
“Oh… Insya Allah
komplit. Mulai dari ensiklopedi, kamus, filsafat, pendidikan, bahkan sastra dan
novel juga banyak.”
“Mmm… ada Siroh
Nabawiyah?” celetuknya.
Aku terdiam di tempatku
berdiri. Membeku. Kembali aku tertohok.
“Perjalanan hidup
Rasulullah sangat menarik bukan untuk kita baca?”
Aku hanya mengangguk.
“Saya yakin Tuan punya
banyak buku Siroh Nabawiyah.” Katanya lagi.
“Oh, tentu.” Aku
berbohong.
“Beliau teladan kita.
Nabi kita. Namnya kita agung-agungkan, bagai seorang idola. Alangkah lucu jika
kita tidak tahu menahu bagaimana kisah hidupnya. Betul bukan?” uangkapnya lagi.
Sungguh, kata-katanya bagai sebilah tombak yang menusuk ke ulu hatiku. Aku
hanya gemetar.
“Oh. Di mana rak buku-buku
Sirohnya?” lelaki itu langsung ke point pertanyaan.
“Sungguh maaf, buku-buku
Siroh koleksi saya dipinjam seorang teman untuk refrensi tugas kuliah, dan
belum dikembalikan.”
“Ooo… Kalau kitab
hadits, tentu Tuan punya.”
“Kitab Hadits?” aku
seperti orang bodoh.
“Iya. Shahih Bukhori
atau Shohih Muslim. Tuan punya, kan? Hadits adalah sumber hukum ke 2 setelah Al-Quran.
Tentu Tuan punya. Saya yakin.”
“Iya. Termasuk kitab
hadits, juga dipinjam teman saya. Ada Riyadhus Sholihin. Jami’us Shaghir juga
ada. Tapi ya itu, semua ada pada teman saya.” Kilahku lagi. Dalam hati aku
berdoa, semoga nama-nama kitab hadist yang kusebutkan tidak ada yang salah.
“Ooo…” kembali lelaki
itu ber’o’ panjang.
Aku sangat lega, lelaki
itu memakluminya. Namun, kebohongan yang telah melesat dari mulutku beberapa
saat yang lalu bagai sebilah cambuk yang terus melecutkan rasa bersalah dan
tidak nyaman. Kami masih berjibaku dengan bukubuku. Membacanya sekilas dan
mengembalikannya ke rak. Hingga beberapa saat kemudian, lelaki itu berpamitan
untuk beristirahat. Aku mengantarnya sampai kamar tamu. Namun sampai di ruang
keluarga mendadak ia berhenti di depan tivi.
“Ini apa? Besar sekali.
Cermin, ya?” kembali ia melontarkan pertanyaan aneh.
“Oh, ini tivi. Biasa
buat hiburan anak-anak.” Kataku.
“Kalau ini?”
“Ini PS, game. Buat
hiburan anak-anak juga.”
“Sangat berguna, ya,
untuk hiburan anak-anak.” Komentarnya bagai sebuah sindiran. Dan aku menelanya
mentah-mentah. Rasanya sepat. Mushola saja tak ada, al-quran usang tak terbaca,
kitab siroh dan hadits tak pernah terpikirkan untuk mengoleksinya, sedangkan
tivi terpajang di ruang keluarga bagai benda kebanggaan yang sangat berharga.
Oo... bagaimana kuhadapi ini?
***
Selepas kuantarkan
lelaki itu ke kamar tamu. Aku ngeloyor ke kamar. Pikranku berkecamuk tidak
karuan. Sekali lagi kutengok istriku yang masih tertidur dengan mulut menganga.
Kali ini, dengkuranya terdengar sangat menjijikan. Aku kembali berjalan keluar
kamar. Kutilik kamar tamu tempat lelaki itu beristirahat, sudah tertutup. Aku
berjalan menuju kamar anak-anak. Mereka juga masih pulas. Maka kuputuskan untuk
keluar rumah. Aku duduk di bangku taman depan. Dingin sekali. Kutilik langit.
Bintang-bintang berpendar bagai hendak menjatuhkan diri. Siapa gerangan lelaki itu?
Aku kembali masuk ke
dalam, ke perpustakaan. Kugeledah satu demi satu buku-buku di sana. Aku sendiri
tak percaya kalau aku tidak punya buku-buku tentang Rasulullah. Nyatanya,
memang tak satupun kudapatkan buku tentang Rasulullah di sana, apalagi kitab
hadits. Aku ingat, aku memang tak pernah membeli kitab hadits, sama sekali. Aku
menggelengkan kepala. Ada yang salah
denganku.
Tiba-tiba aku teringat
buku-buku anakku. Mereka semua kusekolahkan di sekolah islam terpadu. Tentu di
sana ada pelajaran Siroh. Segera aku menghambur ke kamar anakku. Kegeledah meja
belajar mereka. Dan di sana kutemukan buku modul tipis: Siroh Nabawiyah. Serta
merta kupeluk buku itu. Kubuka satu persatu buku itu. Di halaman-halaman awal
kutemukan bab pertama tentang Masyarakat Islam Sebelum Rasulullah, kubaca
sekilas. Kubuka halaman berikutnya, tentang Kelahiran dan Masa Kecil
Rasulullah. Kubaca dengan saksama, tak terasa mataku berair. Kubaca lagi
halaman demi halaman, hingga aku tertidur di kamar anakku sambil mendekap buku
itu.
***
Aku terbangun oleh
suara tarhim yang bagai menyilet telinga. Aku tergeragap. Pertama kali yang
singgah dalam kepalaku adalah lelaki itu. Lelaki berwajah cahaya yang datang
tengah malam tadi. Kutengok kamar tamu tempatnya beristirahat. Masih tertutup
rapat. Barangkali ia kelelahan, pikirku.
Kulihat Nani,
pembantuku, sudah menyiapkan teh hangat di ruang keluarga.
“Sudah bangun, Pak.”
Sapanya.
“Iya. Alhamdulillah, bisa
bangun pagi. Mmm… Nani?”
“Ya, Pak?”
“Tolong tamunya
dibikinkan juga, ya, tehnya!”
“Tamu?” Nani balas
bertanya seperti orang bingung.
“Iya. Semalam bapak ada
tamu. Sekarang masih istrirahat di kamar tamu.”
“Di kamar tamu?” Nani
masih seperti orang ling-lung. “Tapi, barusan saya dari kamar tamu, di sana
tidak ada siapa-siapa.” Jelasnya.
“Ha? Bercanda kamu. Wong semalam saya sendiri kok yang ngater dia ke kamar.”
“Lho? Bener, Pak.
Barusan saya beresin kamar tamu, dan tidak ada siapa-siapa. Tak ada juga bekas-bekas
orang tidur di sana.”
Aku mengernyitkan dahi.
Daripada berdebat kuputuskan untuk langsung beringsut ke kamar tamu, dan Nani benar,
di sana tidak ada siapa-siapa. Buru-buru kutengok kamar mandi, barangkali ia
sedang ke kamar mandi. Tapi di kamar mandi juga tidak ada siapa-siapa. Aku
semakin bingung dan heran. Apa semalam
aku mimpi?
Hingga matahari
meninggi, otakku masih kacau dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ketika
anak-anak berpamitan hendak berangkat ke sekolah. Aku masih seperti orang ling-lung.
Hingga anakku yang paling kecil mengguncang-guncangkan tanganku. Ia berisyarat
ingin membisikkan sesuatu. Maka telingaku kudekatkan pada mulutnya yang mungil.
“Abi,
Abi! Semalam ada tamu, ya?” ia mendesis bagai membisikkan sebuah rahasia. Aku
terhenyak. Kepalaku kembali pada sosok lelaki yang semalam kuakrabi.
“Memangnya adik tahu,
kalau semalam ada tamu?” aku menanggapi pertanyaan itu sambil mengusap wajahnya
yang polos. Ia mengedip-ngedipkan matanya.
Detak jantungku kian
memburu, “Memangnya, adik kenal sama tamu kita semalam?”
“Memangnya Abi gak
kenal?” Ia balik bertanya. Sebelum bibirku bergerak untuk menjawab
pertanyaanya, ia sudah kembali bersuara, “Kalau Abi baca buku sirohku, pasti
Abi kenal…”, sambungnya singkat, sebelum mengecup tanganku, mengucap salam,
lalu melesat berangkat.***