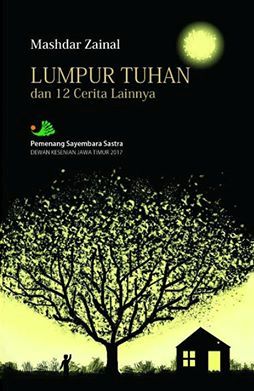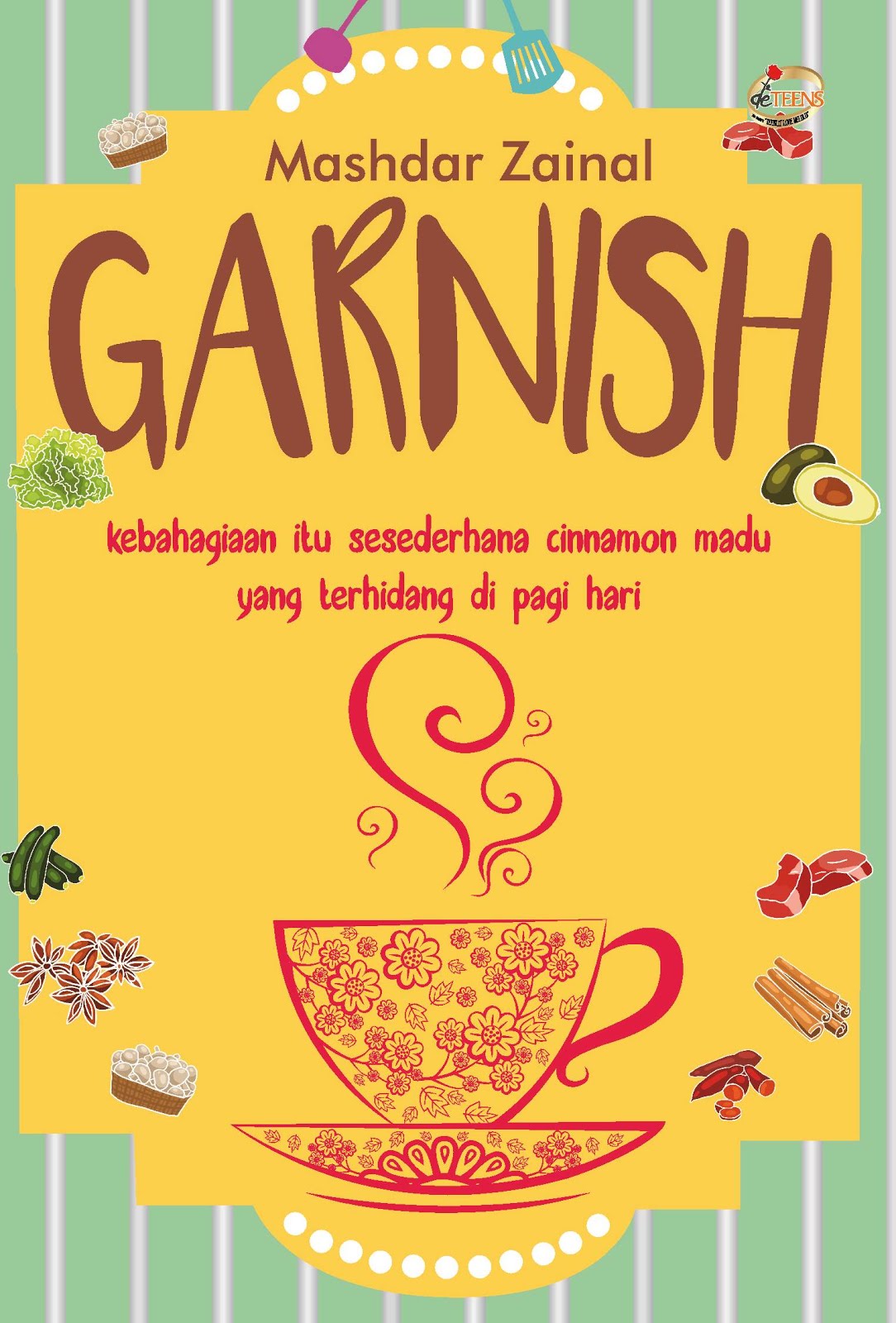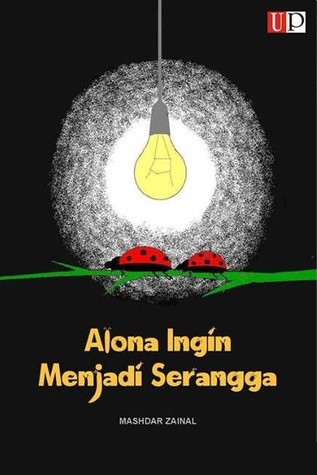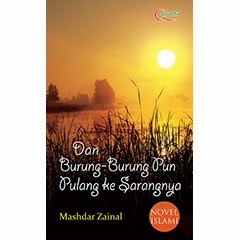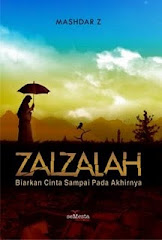Emak terduduk setengah
rebah di ranjang tipisnya. Di sebelahnya teh hangat masih mengepulkan asap.
Beberapa kapsul dan pil bergeletakkan di dalam nampan kecil, menunggu emak
menelannya setelah makan bubur nanti. Dari jendela yang separuh terbuka,
kelambu bergoyang ringan oleh hembusan angin dari ladang kering di sebelah
rumah. Emak melemparkan tatapan kosong ke jendela terbuka itu. Seakan di sana
ada sesuatu yang indah untuk ia raih dan ia jadikan bahan pembuat senyum yang
baru. Emak benar-benar tersenyum.
“Mengapa emak tersenyum-senyum
sendiri?” aku menghampirinya dengan segelas air putih, “obatnya, Mak.”
Emak meletakkan piring
bubur yang tinggal separuh di atas meja, di sebelah ranjangnya, lalu menelan
obat itu dan mendorongnya dengan air putih. Emak menghela napas lega dan
mengucapkan terima kasih.
“Mengapa emak tersenyum-senyum
sendiri?” aku mengulang pertanyaanku.
“Emak hanya bersyukur
bahwa sampai detik ini, emak masih bisa merasakan hembusan angin lewat jendela
kecil itu,” jawab Emak dengan mata berbinar.
Silih aku yang tercenung.
Sudah tiga tahun terakhir ini, setiap kali jelang kurban, jelang lebaran haji,
emak selalu ambruk, sakit sepuhnya selalu kambuh. Jadi, sudah tiga tahun
terakhir ini Emak tidak ikut sholat ied di masjid, Emak tidak ikut menyaksikan
bagaimana ternak kurban di sembelih di halaman masjid. Emak hanya turut mengumandangkan takbir dari
ranjangnya dengan mukena yang tak pernah lepas. Namun, pada siang harinya,
biasanya emak akan memaksakan diri untuk bangun dan memasak daging kurban yang
kami dapat dari panitia kurban.
Biasanya emak akan
menyuruhku membagikan beberapa daging yang sudah ia masak itu ke beberapa
kerabat yang kurang mampu—sama seperti kami. Emak selalu melakukan itu setiap
hari raya kurban—memasak daging yang kami dapat dan membagikannya ke beberapa
kerabat. Emak tak pernah peduli meski para kerabat juga sudah mendapatkan
daging yang sama. Emak tak pernah peduli apa yang akan dilakukan oleh para
kerabat atas daging matang pemberiannya itu. Emak hanya percaya, bahwa hal
tersebut akan mendatangkan berkah baginya. Bagaimana pun Emak termasuk salah
satu tetua kampung yang punya keahlian meramu daging, tidak hanya pada lebaran
kurban saja—sesekali ketika warga kampung menggelar hajatan, mereka kerap
meminta emak untuk menjadi juru masak utama.
“Emak hanya bertawasul,
semoga dengan daging matang yang tidak seberapa itu, Gusti Allah memberi emak
rejeki lebih, supaya emak bisa beli kambing, syukur-syukur sapi buat dikurban,
itu saja.”
Aku sudah lupa, kapan
pertama kali emak menuturkan kata-kata itu. Usia Emak kini sudah masuk enam
puluhan, dan sampai detik ini kami belum dikaruniai rejeki lebih untuk bisa
membeli binatang kurban yang hanya setahun sekali itu. Sejatinya, emak punya
dua mimpi yang tak pernah secara gamblang ia tuturkan. Mimpi emak yang pertama
adalah pergi ke mekah, namun karena emak tahu bahwa mimpi itu terlalu
tinggi—meski bukannya tidak mungin, emak lebih memilih untuk menyimpan mimpi
itu dalam-dalam hingga tak pernah membahasnya. Mimpi emak yang kedua ialah ia
bisa membeli ternak untuk kurban yang hanya setahun sekali itu. Bagi Emak, mimpi yang kedua itu lebih mudah
untuk ia raih—meski tidak semudah yang dibayangkannya.
Berkali-kali emak
menabung, tapi selalu saja, tabungannya itu ia pecah setiap kali kami ada
keperluan mendesak. Seperti tiga tahun lalu saat Uus—istriku, harus masuk rumah
sakit karena gejala thypus. Emak terpaksa mengeluarkan tabungannya untuk
menambal kekurangan biaya rumah sakit selama tiga hari—yang menurut kami
jumlahnya lumayan besar.
Setahun lalu, ketika
istriku melahirkan, emak juga terpaksa merogoh tabungannya, karena uangku
sendiri tidak cukup untuk biaya persalinan. Terkadang aku merasa sangat malu
pada diriku sendiri. Aku sudah bilang pada Emak, bahwa aku berjanji akan
mengganti uangnya yang telah kami pakai, tapi emak malah bilang, “soal uang tak
perlu dibahas lagi. Gusti Allah yang akan kasih ganti.”
Dan entah mengapa, jelang
lebaran haji kali ini, aku melihat wajah emak semakin layu, tubuhnya semakin
kurus, dan ia tampak lebih renta. Terlebih setelah sakit tahunan itu kembali
menderanya. Maka, dalam hati, aku sudah berjanji, bahwa tahun ini aku akan
membelikan emak seekor kambing. Aku sudah mulai menabung sedikit-sedikit.
Hingga dua hari jelang penyembelihan, uang yang kusisihkan di kantongku telah
terkumpul sebanyak 750 ribu. Aku memutar otak dan berpikir, apakah ada kambing
yang layak dan memenuhi persyaratan kurban dengan harga segitu.
Aku sudah berkeliling
dari satu tempat ke tempat yang lain, dan aku tak menemukan kambing kurban
dengan harga 750 ribu. Aku merasa bahwa diriku hanya jadi bahan tertawaan para
makelar kambing.
“Bahkan anak kambing pun
belum dapat dengan uang segitu,” kata salah satu pedagang dengan tawa sinis,
“Kambing kurban, paling murah itu setidaknya satu, Mas, satu juta.”
Aku pun kembali ke rumah
dengan lesu. Kulihat emak masih terbaring di ranjangnya dengan mata terpejam,
dengan mukena yang tak pernah lepas.
Esok harinya aku kembali
berkeliling, dengan tambahan uang 250 ribu dari istriku. Jadi, uang yang kubawa
untuk seekor kambing adalah satu juta rupiah. Aku berangkat dengan sesungging senyum,
dengan uang tambahan itu mungkin aku akan dapat seekor kambing dari seorang
pedagang yang dermawan. Tak kurang dari lima tempat aku datangi, dan aku tetap
tidak mendapatkan kambing dengan harga satu juta rupiah. Ada satu kambing dengan harga satu juta, meski kambing itu telah memenuhi persyaratan untuk kurban, tapi kambing
itu terlalu kecil dan kurus dan tampak kurang sehat, meski si pedagang mengatakan bahwa
kambingnya baik-baik saja dan keadaanya memang seperti itu.
Akhirnya aku memilih
untuk mencari kambing di tempat lain. Dengan keadaan hampir putus asa, aku
mendatangi sebuah tenda di mana puluhan kambing mengembek dan telah siap untuk
dikurban. Seorang lelaki dengan perawakan sedang, dengan wajah jernih dan
sedikit jambang, menyambutku dengan
sumeringah. Ia menceritakan kondisi kambing-kambing yang ia jual berikut harga-harganya.
Kambing-kambing yang ia jual semuanya gemuk-gemuk dan tampak sangat prima, aku
sudah menduga harga kambing-kambing itu, dan aku sudah siap gagal untuk ke
sekian kalinya. Aku belum sempat menawar satu pun dari kambing itu, namun aku
sudah berniat untuk meninggalkan tempat itu.
“Mengapa Anda terburu-buru,
tidakkah Anda ingin melihat-lihat dulu, soal harga bisa dirundingkan,” kata
lelaki jernih itu dengan seulas senyum.
“Saya tahu, uang saya tak
akan cukup meski harga kambing itu sudah Tuan turunkan, makanya lebih baik saya
pergi saja, saya sudah berkeliling sejak kemarin dan saya memang sedang bermimpi
bisa mendapatkan kambing bagus dengan harga segitu,” kataku apa adanya.
Lelaki itu melambaikan
tangannya, menyuruhku duduk di sebelahnya, “Memangnya berapa uang yang Anda
bawa?”
“Satu juta,”
jawabku singkat.
Lelaki itu tersenyum,
tapi bukan senyum sinis, “Coba Anda ceritakan, mengapa Anda bersikeas untuk
mendapatkan seekor kambing, sedangkan Anda tahu uang Anda tak akan cukup.”
Dengan tenang aku mulai
menceritakan semuanya, tentang emak, tentang kebiasaannya setiap lebaran kurban
tiba, tentang mimpi-mimpinya, sampai akhirnya tentang mengapa aku bersikeras
ingin mendapatkan kambing dengan uang alakadarnya. Setelah mendengar ceritaku,
lelaki itu menepuk pundakku dan mengatakan, “Kau boleh membawa satu kambingku,
yang mana pun.”
Mendadak tubuhku gemetar
mendengarnya, aku nyaris ambruk karena tak percaya, aku terkikik sekilas, “Anda
bercanda…”
“Saya tidak bercanda,” lelaki
itu itu malah menuntunku untuk memilih kambing yang paling besar dan paling gemuk.
“Tapi uangku cuma satu juta,” kataku masih dengan suara gemetar karena tak percaya. Aku
menyerahkan gumpalan uang yang kuyu pada lelaki itu. Tapi lelaki itu menolak.
“Saya akan menerima uang
itu nanti, setelah Anda membawa kambing itu ke hadapan ibu Anda.”
Aku semakin bingung.
Namun lelaki itu menyuruhku untuk bersegera membawa kambing itu. Katanya,
supaya aku percaya bahwa ia sunguh-sungguh dan aku tidak sedang bermimpi. Maka,
dengan tangan dan kaki gemetar aku terus berjalan dan terus-menerus menengok ke
arah kambing gemuk yang mengembek di belakangku. Aku masih takut jika kambing
itu hanya sebuah mimpi dan kemudian aku terbangun dengan tangan kosong. Namun,
sampai di depan rumah, tepatnya sampai di depan kamar emak—aku sengaja membawa
kambing itu sampai ke kamar emak, kambing itu masih utuh. Aku tak sabar untuk
menceritakan semuanya kepada emak.
“Ya. Kambing itu buat
emak. Buat kurban, atas nama emak,” tuturku dengan dada sedikit gugup karena
bahagia. Emak tak bisa berkata sepatah kata pun. Ia hanya menangis. Turun dari ranjangnya—masih
dengan mukenanya, dan memeluk kambing itu erat-erat. Aku dan istriku, juga
emak, mungkin masih tak percaya. Tapi kami semua percaya, bahwa Gusti Allah
punya cara yang tak pernah diduga-duga manusia.
Aku tak sabar untuk
kembali kepada lelaki itu dan mengucapkan terima kasih dan menceritakan
ekspresi emak saat kambing itu kubawa ke hadapannya. Namun, ketika aku sampai
di tempat semula, aku tidak mendapati apapun. Di tempat itu tidak ada tenda,
tidak ada orang berjualan kambing atau apapun. Bahkan bekas maupun bau-bau
kambing pun tidak ada. Sama sekali. Lenyap. Seperti ditelan tanah. Ketika
kutanya pada orang-orang yang mukim disekitar situ, mereka bilang bahwa di
tempat itu memang tidak ada orang berjualan kambing atau apapun. Tempat itu
hanya tanah kosong yang tidak dipelihara.
Dengan tubuh gemetaran, dahi
berkeringat dan telapak tangan yang tiba-tiba dingin, aku bergegas kembali ke
rumah dan bertanya-tanya, apakah kambing itu masih nyata. Dan sesampainya di
rumah, aku melihat emak—dengan wajah sumeringah, seolah tidak sedang sakit—tengah
memberi makan kambing itu di halaman rumah. Kambing yang sama dengan yang
kutuntun beberapa waktu lalu, kambing yang besar dan gemuk. Mulutku masih
tercekat, ketika Emak berteriak, “Kapan kambingnya mau di bawa ke masjid?”***
Malang, Jelang Kurban, Oktober 2013